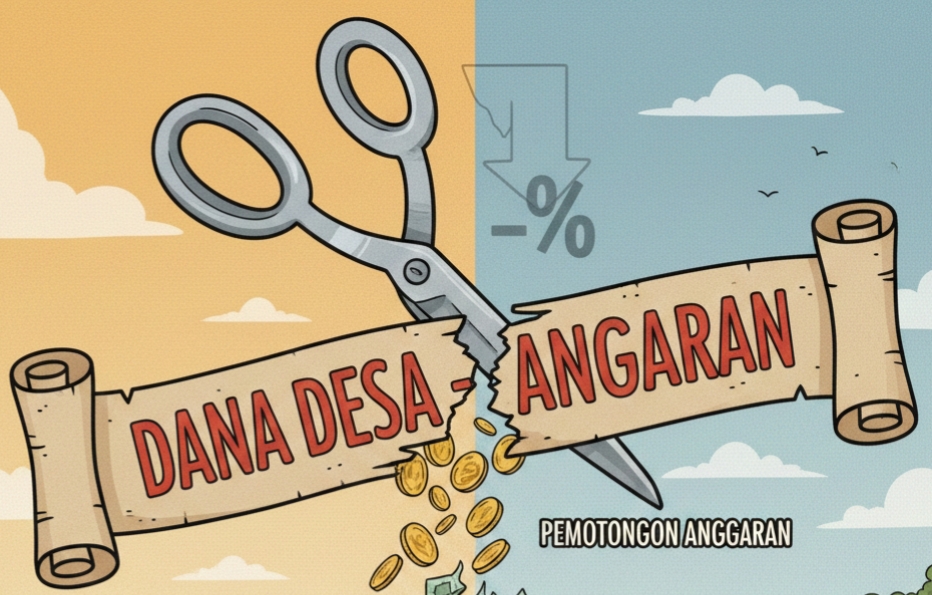![]()
(Oleh: Undang Herman, Aktivis Sosial dan Kebijakan Publik)
Artikel,TRIBUNPRIBUMI.com – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXI/2025 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah tahun 2029 adalah fakta konstitusional yang tidak bisa dibantah. Putusan itu final dan mengikat. Namun dalam demokrasi, sesuatu yang final secara hukum belum tentu final dalam ruang kritik publik.
Dampak paling nyata dari putusan tersebut adalah perpanjangan masa jabatan anggota DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota selama kurang lebih dua hingga dua setengah tahun. Di sinilah letak persoalan yang tidak sederhana. Demokrasi dibangun di atas prinsip periodisasi kekuasaan dan mandat rakyat yang dibatasi waktu.
Sementara lima tahun adalah kontrak politik antara rakyat dan wakilnya. Ketika masa itu diperpanjang tanpa pemilu, maka pertanyaan mendasar pun muncul: apakah ini penguatan demokrasi atau justru pengurangan kedaulatan rakyat?
Demokrasi dan Kontrak Politik
Pemilu bukan sekadar agenda rutin lima tahunan. Ia adalah mekanisme evaluasi. Ia adalah forum penghakiman rakyat terhadap kinerja wakilnya. Ketika pemilu dipisahkan dan berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan tanpa pemilihan ulang, maka mekanisme evaluasi itu tertunda.
Dalam teori demokrasi modern, legitimasi kekuasaan tidak hanya lahir dari prosedur hukum, tetapi juga dari persetujuan berkala rakyat melalui pemilu. Jika masa jabatan diperpanjang tanpa persetujuan langsung dari pemilih, legitimasi tersebut menjadi problematis secara moral dan politik.
Saya tidak mempersoalkan kewenangan MK. Namun yang patut dikritisi adalah dampak sosial dan politik dari putusan ini. Apakah Mahkamah telah mempertimbangkan secara matang aspek sosiologis dan politik di daerah? Ataukah terlalu jauh memasuki ranah open legal policy yang seharusnya menjadi domain pembentuk undang-undang?
Untung Elit, Rakyat Menunggu Kepastian
Bagi sebagian anggota DPRD, perpanjangan masa jabatan tentu terasa seperti berkah politik. Tanpa perlu kembali ke rakyat untuk meminta mandat baru, kursi kekuasaan tetap aman. Stabilitas posisi terjaga. Jaringan politik semakin mapan.
Namun di sisi lain, rakyat tidak mendapatkan kesempatan untuk menilai dan menentukan ulang apakah wakilnya masih layak dipertahankan atau tidak. Dalam kondisi di mana citra DPR dan DPRD sedang tidak berada pada titik terbaik, kebijakan ini bisa menjadi bahan bakar ketidakpercayaan.
Kita tidak bisa menutup mata bahwa publik kerap memandang lembaga legislatif dengan skeptis. Isu absensi rapat, pembahasan perda yang tidak aspiratif, hingga konflik kepentingan menjadi catatan panjang. Dalam situasi seperti itu, perpanjangan masa jabatan tanpa pemilu berpotensi memperkuat persepsi bahwa sistem lebih berpihak pada elit daripada rakyat.
Potensi “Raja-Raja Kecil” di Daerah
Yang lebih mengkhawatirkan adalah kemungkinan lahirnya konsolidasi kekuasaan yang terlalu kuat di daerah. Masa jabatan yang lebih panjang tanpa tekanan elektoral dapat menciptakan ruang nyaman bagi praktik politik transaksional.
Jika tidak diawasi secara ketat, tambahan waktu ini bisa dimanfaatkan bukan untuk memperbaiki kinerja, tetapi untuk memperkuat jaringan kekuasaan, memperluas pengaruh, bahkan membangun dinasti politik. Demokrasi lokal yang seharusnya partisipatif bisa berubah menjadi arena dominasi kelompok tertentu.
Kita juga melihat gejala pembangkangan terhadap instruksi presiden (Inpres) atau peraturan menteri (Permen) di beberapa daerah. Jika lembaga legislatif daerah merasa posisinya relatif aman karena masa jabatan diperpanjang, potensi resistensi terhadap kebijakan pusat bisa semakin menguat. Ini bukan sekadar persoalan teknis pemilu, melainkan soal tata kelola negara.
Dimensi Sosiologis yang Terabaikan
Putusan hukum harus mempertimbangkan dampak sosialnya. Rakyat di daerah tidak sedang memikirkan sinkronisasi jadwal pemilu. Mereka memikirkan harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.
Ketika elite politik berbicara soal desain pemilu, rakyat berbicara soal kesejahteraan. Jika perpanjangan masa jabatan tidak diiringi dengan peningkatan kinerja nyata, maka keputusan ini akan dipersepsikan sebagai keuntungan sepihak.
Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang sensitif terhadap rasa keadilan publik. Jika rakyat merasa haknya untuk mengevaluasi wakilnya ditunda, maka akan muncul rasa keterasingan dari proses politik.
Jalan Tengah: Akuntabilitas Tanpa Kompromi
Jika perpanjangan masa jabatan memang menjadi konsekuensi konstitusional, maka satu-satunya jalan untuk menjaga legitimasi adalah dengan memperkuat akuntabilitas.
DPRD harus membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya. Transparansi kinerja harus ditingkatkan. Evaluasi internal harus diperketat. Jangan sampai tambahan dua tahun hanya menjadi perpanjangan kenyamanan.
Rakyat tidak alergi pada kebijakan. Rakyat hanya menuntut keadilan dan pertanggungjawaban. Jika masa jabatan diperpanjang, maka kualitas kerja pun harus ditingkatkan. Jika tidak, sejarah akan mencatat bahwa demokrasi pernah diperpanjang, tetapi kepercayaan rakyat justru dipersingkat.
Penutup: Demokrasi Tidak Boleh Kehilangan Ruh
Demokrasi bukan hanya soal kepastian hukum. Demokrasi adalah tentang kedaulatan rakyat. Hukum yang tidak sensitif terhadap rasa keadilan publik berisiko kehilangan legitimasi moralnya.
Putusan MK mungkin final. Tetapi kritik publik adalah bagian dari demokrasi itu sendiri. Kita tidak sedang melawan konstitusi. Kita sedang mengingatkan bahwa konstitusi dibuat untuk menjaga kedaulatan rakyat, bukan sekadar mengatur mekanisme kekuasaan.
Jika perpanjangan ini benar-benar digunakan untuk memperkuat pelayanan kepada rakyat, maka sejarah akan memakluminya. Namun jika ia hanya menjadi perpanjangan kekuasaan elit, maka rakyatlah yang akan menjerit dan menanggung akibatnya.
Demokrasi tidak boleh sekadar diperpanjang.
Demokrasi harus terus dipertanggungjawabkan.